TikTok? Jangan Terlalu Diromantisasi
Penulis: Achmad Fauzan Syaikhoni
Editor: Thiara
Setidaknya, di lingkup pertemanan saya; mereka mengepos story dari konten TikTok bertajuk mental health dan asmara—kebanyakan untuk menyindir kawan satu circle-nya, gebetan, pacar, bahkan orang tua mereka. Parahnya lagi, mereka ini dengan pedenya ngasih caption secara membabi buta bak orang paling benar sedunia. Inilah yang membuat saya kadang risih ngeliat kenaifan mereka dalam menggunakan media sosial.
Yah memang saat ini media sosial seperti TikTok enggak bisa lepas dari kehidupan kita. Malah, sekarang hampir semua informasi bisa didapat melalui TikTok. Justru karenanya kita perlu sadar bahwa TikTok sebagai produk manusia juga punya kelemahan. Tentu saja kita sebagai pengguna enggak bisa memperbaiki kelemahan itu. Namun, kita punya akal, setidaknya ada kesadaran bahwa jangan terlalu meromantisasi TikTok bak Tuhan Sang Maha Benar.
Lah, emangnya kenapa? Kan, TikTok juga berisi beberapa ahli yang bisa dijadikan sumber informasi? Nah, berikut beberapa alasan kenapa kita sebagai anak muda jangan terlalu meromantisasi TikTok walaupun di sana berisi banyak ahli yang potensial jadi sumber informasi.
Rentan miskonsepsi karena gangguan mental
Kiranya sudah menjadi fakta umum kalau anak muda atau masa remaja itu kondisinya cenderung emosional sebab perubahan hormon dan fisiknya. Karena itu, enggak heran kalau ada informasi pada konten TikTok yang terkesan relate, mereka langsung reaktif buat ngeshare informasi tersebut tanpa mengindahkan akal budinya buat menelaah terlebih dahulu.
Nah, dalam kajian psikologi, kondisi semacam itu sebenarnya masuk dalam kategori gangguan mental. Eits … jangan marah dulu, gangguan mental itu enggak hanya tersemat pada ODGJ aja. Orang-orang normal pun pasti pernah mengalami gangguan mental.
Dari definisinya sendiri, gangguan mental adalah ihwal apapun yang menganggu pikiran, perasaan, perilaku atau bahkan ketiganya. Jadi, mulai sekarang jangan sombong-sombong kalau ketemu ODGJ, bisa jadi kalian itu sama.
Di konteks ini, gangguan mental yang dialami anak muda ketika menyebar konten-konten TikTok—yang penuh kebohongan itu termasuk pada gangguan mental—yang dalam bukunya Rolf Dobelli berjudul The Art of Thinking Clearly, disebut dengan bias konfirmasi. Singkatnya, bias konfirmasi ialah ketika seseorang mengambil informasi hanya berdasarkan keyakinannya, dan mengabaikan hal-hal lain yang sebenarnya juga berhubungan.
Itulah mengapa anak muda potensial mengalami miskonsepsi ketika menyebar konten TikTok. Sebab mereka hanya “akan” peduli dengan informasi yang mendukung pikiran dan perasaannya. Sebaliknya mereka akan mengabaikan informasi lain yang jika dihubungkan akan membatalkan keyakinannya terhadap informasi tersebut. Gimana? Ngerti dewe kan barange!
Melihat kebenaran informasi hanya berdasarkan popularitas
Sekarang, begitu banyak para influencer yang mengemuka di TikTok. Mulai dari yang muda hingga dewasa, mereka semuanya bebas memproduksi konten jenis apapun tanpa terikat dengan profesinya sebagai siapa. Walaupun si influencer bukan seorang psikolog, tapi bisa aja yang dibicarakannya membuat banyak orang percaya, sekalipun omongan tersebut enggak berdasarkan data ataupun sumber informasi yang kredibel. Karena yang terpenting di media sosial— termasuk TikTok—adalah se-popular apa dia atau seberapa banyak followers yang dia miliki, maka otomatis semua pembicaraannya adalah benar.
Itulah yang menyebabkan anak muda yang cenderung emosional akan terjerumus pada kebodohan. Mereka biasanya punya idola masing-masing di TikTok. Sehingga kalau idolannya bicara apapun, mereka akan mengambilnya sebagai kebenaran, bahkan enggak jarang mereka turut membela secara membabi buta kalau ada yang membantah idolanya. Ini kiranya bukan lagi bodoh, sebab orang bodoh masih punya otak meskipun kadang konslet.
Dalam kajian psikologi pun itu termasuk dalam gangguan mental. Seorang psikolog asal Amerika, Edward Thorndike, dalam artikelnya berjudul “A Constant Error in Psychological Ratings”, menyebut ini sebagai hallo effect. Psikolog itu bilang bahwa seseorang akan terlihat bodoh, ketika dia menganggap suatu informasi dari A itu benar, hanya karena A dari awal udah punya citra positif.
Kalau kalian punya kawan semacam itu, jangan bawa ke psikolog. Bawa aja ke spesialis bedah saraf. Siapa tahu saraf otaknya putus.
Takut ketinggalan informasi aktual
Seperti yang umum diketahui, TikTok ada istilah yang namanya fyp. Fyp ini secara garis besar menandakan seperti apa konten-konten yang sedang tren. Kalau tren kontennya tentang diselingkuhi, maka hampir dipastikan akan muncul kata-kata tentang perselingkuhan. Atau trennya mengenai salah satu penyakit mental anak muda, maka juga akan muncul nasehat-nasehat yang membersamainya.
Salah satu kawan pernah saya interogasi yang pada saat itu trennya tentang bipolar. Dan dia bener-bener gobloknya minta ampun, alasan dia menganggap dirinya terkena bipolar ternyata karena saat malam hari dia kesepian ditinggal pacarnya lembur kerja tiap hari. Kan, tai! Lah wong emang nganggur; kerjaannya hapean doang, yang disalahin bipolarnya.
Itu juga masalah besar dalam psikologi, yang disebut sama Pattrick J. McGinnis dalam bukunya berjudul Fear of Missing Out, sebagai kondisi di mana seseorang merasa cemas kalau enggak segera mengikuti hal-hal yang sedang viral. Dan menurutnya, seseorang yang rentan terkena FOMO itu kebanyakan adalah anak muda.
Konten di media sosial/tiktok enggak cukup utuh sebagai informasi
Saya mungkin salah satu dari sekian orang yang menganggap kalau konten-konten di TikTok itu enggak cukup utuh dibuat sebagai suatu informasi. Sebab, semua konten yang mengemuka pasti enggak lebih dari 250 kata. Saya beranggapan seperti itu karena suatu informasi pastilah sifatnya informatif; mencerahkan, dan sesuatu yang mencerahkan pasti mempunyai banyak pecahan-pecahan. Bahkan sekadar artikel yang berisi 1000 kata pun kadang sarat akan disinformasi.
Makanya, kenapa sering orang bilang ketika mengatasi hoaks itu haruslah melakukan check and recheck. Ini lagi-lagi juga termasuk dalam gangguan mental yang oleh psikolog sosial, David Dunning dan Justin Kruger dalam artikelnya berjudul “Why People Fail to Recognize Their Own Incompetence”, disebut dengan Dunning-Kruger-Effect. Kedua psikolog itu bilang, bahwa ketika seseorang hanya memiliki sekelumit saja dari sebuah informasi yang kompleks, dia akan sangat percaya diri padahal sebenarnya bodoh.
Itulah tadi alasan-alasan mengapa kita sebagai anak muda jangan terlalu meromantisasi TikTok. Sebenarnya masih banyak alasan-alasan lain yang memungkinkan kawan-kawan muda secara enggak sadar jadi bodoh ketika terjun di media sosial. Tapi 4 poin tadi saya rasa cukup mewakili masalah kebanyakan anak muda sekarang.
Semoga dengan adanya ini, kita semua, khususnya anak muda, bisa lebih bijak lagi menggunakan media sosial, bukan sebagai sumber informasi, melainkan sebagai alat untuk mengantarkan kita pada keingintahuan yang lebih mendalam.
Achmad Fauzan SyaikhoniManusia setengah matang, yang sedang fakir pengetahuan. Kalau mau menyumbang pengetahuan, bisa kirim lewat Instagram saya @zann_sy

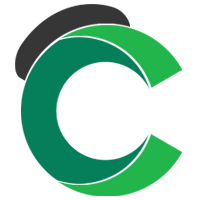
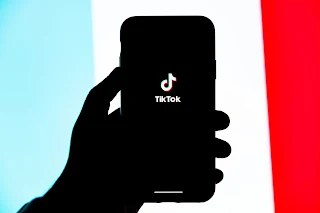

Posting Komentar