Kata "Peh" dan "Biuh" dari Keresidenan Kediri: Begini Analisis Semiotikanya Serta Hubungannya dengan Kata "Cuk"
 |
| iNews |
Penulis: Achmad Fauzan Syaikhoni
Editor: Fatio Nurul Efendi
Cangkeman.net - Sebagai calon lulusan sarjana komunikasi, belakangan ini saya tertarik untuk meneliti ragam bahasa yang ada di daerah tempat saya kuliah, Kediri. Salah satu dari banyaknya ragam bahasa di Kediri adalah kata “peh” dan “biuh”. Sebenarnya saya awal-awal jadi pendatang di Kediri menganggap kata “peh” dan “biuh” itu B aja, nggak ada istimewa-istimewanya.
Tapi belakangan ini di jagat media sosial, kedua kata itu nyaris nggak luput di pesan-pesan WhatsApp, caption story, ataupun komentar-komentar netizen Indonesia. Bahkan, kawan-kawan saya yang di Mojokerto, Sidoarjo, Gresik dan Surabaya pun percakapannya penuh dengan kata “peh” dan “biuh”. Heran betul saya.
Melihat fenomana itu, saya seketika berpikir, bagaimana ya masa depan “cuk” jika sekarang “peh” dan “biuh” menghegemoni model komunikasi sosial masyarakat kita? Jika demikian, lantas apakah kemudian nilai sosio-budaya kita yang plural ini perlahan akan didominasi oleh nilai sosio-budaya Kediri? Sungguh, saya pikir ini harusnya jadi peluang besar bagi para peneliti untuk meningkatkan karya ilmiahnya di tingkat scopus.
Namun, karena saya bukan peneliti, bahkan masih ‘calon’ sarjana, maka yang bisa saya lakukan hanyalah jadi peneliti abal-abal dulu. Tapi tenang saja, walaupun abal-abal, saya tetap berusaha menjunjung tinggi nilai akademis saya, yang dalam hal ini akan saya buktikan lewat analisis kata “peh” dan “biuh” dengan pendekatan semiotika.
“Kenapa kok pakai semiotika?”
Yah terserah saya. Lagian juga cocok-cocok aja, kok. Kalau nggak percaya, mari sama-sama mengenal teori semiotika terlebih dahulu secara saksama, dan saya jamin kita akan paham dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Cangkeman.net - Sebagai calon lulusan sarjana komunikasi, belakangan ini saya tertarik untuk meneliti ragam bahasa yang ada di daerah tempat saya kuliah, Kediri. Salah satu dari banyaknya ragam bahasa di Kediri adalah kata “peh” dan “biuh”. Sebenarnya saya awal-awal jadi pendatang di Kediri menganggap kata “peh” dan “biuh” itu B aja, nggak ada istimewa-istimewanya.
Tapi belakangan ini di jagat media sosial, kedua kata itu nyaris nggak luput di pesan-pesan WhatsApp, caption story, ataupun komentar-komentar netizen Indonesia. Bahkan, kawan-kawan saya yang di Mojokerto, Sidoarjo, Gresik dan Surabaya pun percakapannya penuh dengan kata “peh” dan “biuh”. Heran betul saya.
Melihat fenomana itu, saya seketika berpikir, bagaimana ya masa depan “cuk” jika sekarang “peh” dan “biuh” menghegemoni model komunikasi sosial masyarakat kita? Jika demikian, lantas apakah kemudian nilai sosio-budaya kita yang plural ini perlahan akan didominasi oleh nilai sosio-budaya Kediri? Sungguh, saya pikir ini harusnya jadi peluang besar bagi para peneliti untuk meningkatkan karya ilmiahnya di tingkat scopus.
Namun, karena saya bukan peneliti, bahkan masih ‘calon’ sarjana, maka yang bisa saya lakukan hanyalah jadi peneliti abal-abal dulu. Tapi tenang saja, walaupun abal-abal, saya tetap berusaha menjunjung tinggi nilai akademis saya, yang dalam hal ini akan saya buktikan lewat analisis kata “peh” dan “biuh” dengan pendekatan semiotika.
“Kenapa kok pakai semiotika?”
Yah terserah saya. Lagian juga cocok-cocok aja, kok. Kalau nggak percaya, mari sama-sama mengenal teori semiotika terlebih dahulu secara saksama, dan saya jamin kita akan paham dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Mengenal semiotika dalam waktu kurang dari satu menit
Teori “semiotika” itu secara kebahasaan gampangnya adalah teori tentang tanda/makna bahasa. Kalau kalian ketik di mesin pencarian google kata “teori semiotika”, maka pasti kalian akan kebingungan karena di sana disuguhkan banyak sekali model semiotika. Dari mulai modelnya almukarrom Roland Barthes, romo Charles Sanders Peirce, hingga propesor John Fiske.
Semua model dari blio itu rumit, dan saya pun nggak paham-paham amat, hanya hafal nama-namanya aja. Tapi ada satu model yang sangat gampang, yaitu dari sang pencetus awal nama ‘semiotika’, panggil saja almukarrom sayyidina Ferdinand De Saussure.
Teorinya gampang sekali, bahkan tanpa kuliah dan membaca buku pun saya rasa kita semua udah tahu. Jadi, menurut Saussure, untuk mengetahui suatu makna menggunakan teori atau analisis semiotika, kita harus menggalinya dengan dua unsur, yaitu penanda (signifier) dan petanda (signified).
Contohnya begini, “maaf, ya, kamu terlalu baik buat aku”, perkataan itu adalah penanda. Sementara yang petanda adalah, “aku nggak mau hidup bersamamu, karena kamu jelek dan nggak punya iphone, tapi karena aku takut menyakitimu, maka aku bilang saja bahwa kamu terlalu baik buat aku”, itulah semiotika. Gampang, kan? Mari kita menuju pembahasan intinya.
Kata “peh” sebagai kata imbuhan bermakna negatif
Walaupun saya bukan asli dari warga keresidenan Kediri, tapi saya tahu betul perkara “peh” dan “biuh” ini dari kawan-kawan saya yang asli keresidenan Kediri. Oh, ya, for your information aja, istilah keresidenan Kediri ini maksudnya adalah pembagian wilayah administratif yang terdiri dari Kabupaten Kediri, Trenggalek, Blitar, Tulungagung, dan Nganjuk. Jadi, kata “peh” dan “biuh” pasti udah mendarah daging dalam perbendaharaan kata warga atau anak muda keresidenan Kediri.
Oke, balik ke pembahasan. Menurut kawan saya, sebut saja namanya Ihya’, bahwa “peh” itu merupakan kata imbuhan yang bermakna negatif. Misalnya perkataan, “awakmu kok tuolol, sih, peh!”, atau yang lain seperti, “aku wingi i guoblok lo, ape tuku bensin i tapi malah aku melu antrian solar, peh!”. Jadi, kata “peh” itu biasa dipakai sebagai kata imbuhan di akhir kalimat.
Lalu, kenapa bisa bermakna negatif? Nah, mari kita bedah secara semiotika.
Bunyi perkataan tadi, “aku wingi i guoblok lo, ape tuku bensin i tapi malah aku melu antrian solar, peh!”, itu adalah ‘penanda’ sebagai kata imbuhan. Sementara ‘petandanya’, seseorang itu sadar atas kegoblokannya sendiri karena merasa dirinya nggak mampu membedakan mana antrian bensin dan mana antrian solar. Jadi, berdasarkan semiotika, saya menyimpulkan bahwa kata “peh” itu muncul dari kondisi mental yang ngerasa jengkel, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Di sinilah titik negatifnya.
Makanya, kalau kalian hendak menggunakan kata “peh” dalam sebuah kalimat, maka tentukan dulu, apakah mental kalian sedang merasa jengkel atau nggak. Jangan sampai keliru, jangan sampai menyalahi kaidah tata bahasa keresidenan Kediri. Bahaya!
Kata “biuh” sebagai kata imbuhan bermakna hiperbola
Secara popularitas, rasa-rasanya kata kedua asal keresidenan Kediri ini yang paling popular adalah kata “biuh”. Hampir di tiap kejadian atau suasana tertentu, kata “biuh” ini laris jadi modal komunikasi sosial masyarakat Indo, khususnya anak muda sekarang. Penasaran kenapa hal itu bisa terjadi? Mari ikuti analisis saya.
Lagi-lagi supaya ada unsur penelitiannya, saya harus mengambil referensi dari kawan saya yang namanya Ihya’ tadi. Kata dia, “biuh” itu adalah kata imbuhan yang punya makna hiperbola. Misalnya kalimat, “biiiuuhh… kowe buluk ngunu kok iso oleh pacar ayu!”, atau perkataan yang lain, “biuh biuuuhhh… uwapik tenan kui pemandangan e!”. Iya, pokoknya kata “biuh” itu lebih seru digunakan, entah ketika jengkel, takjub, atau hendak mengolok-olok orang. Tapi ingat, penempatan “biuh” selalu di awal kalimat, bukan di akhir seperti “peh”.
Terus, letak hiperbolanya di mana? Lagi-lagi inilah pentingnya menganalisis dengan pendekatan semiotika.
Coba perhatikan kedua kalimat contoh di atas tadi, keduanya secara ‘penanda’ adalah perkataan yang menunjukkan kata seruan terhadap suatu hal. Sementara secara ‘petanda’, kedua kalimat itu bermakna sebagai bumbu-bumbu semacam micin atau royco atas apa yang sedang dirasakan, dilihat, bahkan diraba. Jadi, ketika mengatakan suatu hal yang kesannya seru, itu rasa-rasanya nggak lengkap kalau nggak dilebih-lebihkan dengan menambahkan kata, “biiiuhhh…” atau di-double sampai berbunyi, “biuh biuuuhhhh…..”. Kira-kira begitulah analisis semiotikanya.
“Peh” dan “biuh” sebagai pelengkap kata “cuk”
Dari analisis dan penjelasan terkait “peh” dan “biuh” tadi, kira-kira apakah kedua kata itu akan mengancam eksistensi kata “cuk” sebagai satu-satunya kata umpatan paling popular sepanjang tahun?
Sebagai warga tulen Mojokerto-an yang sedari kecil mengadopsi kata “cuk”, saya nggak menemukan potensi ancaman itu. Justru dengan popularnya “peh” dan “biuh”, saya rasa malah melengkapi horizon kata “cuk” sebagai kata yang memuaskan birahi, mental, dan hasrat saya untuk mengumpat. Nggak percaya? Mari kita terapkan sama-sama.
Kalau ketiganya digabung, maka bunyinya akan begini, “biuh biuuhhh…. baliho nek dalan iki kok akeh tenan cuk, jan-jane kui arep nyaleg opo arep dodolan rai, sih, peh!”.
Nah, kalau itu nggak perlu dianalisis menggunakan teori semiotika, sebab ketika kita mengatakannya dengan penuh semangat Nasionalisme pun udah jelas, bahwa mengumpat dengan komposisi kata peh, biuh, dan cuk adalah sebagian wujud dari pancasila. Jadi, kesimpulan dari penelitian saya ini mengemukakan, bahwa jangan anggap peh dan biuh sebagai ancaman, tapi jadikanlah sebagai pelengkap umpatan khas warga negara Indonesia,
Semua model dari blio itu rumit, dan saya pun nggak paham-paham amat, hanya hafal nama-namanya aja. Tapi ada satu model yang sangat gampang, yaitu dari sang pencetus awal nama ‘semiotika’, panggil saja almukarrom sayyidina Ferdinand De Saussure.
Teorinya gampang sekali, bahkan tanpa kuliah dan membaca buku pun saya rasa kita semua udah tahu. Jadi, menurut Saussure, untuk mengetahui suatu makna menggunakan teori atau analisis semiotika, kita harus menggalinya dengan dua unsur, yaitu penanda (signifier) dan petanda (signified).
Contohnya begini, “maaf, ya, kamu terlalu baik buat aku”, perkataan itu adalah penanda. Sementara yang petanda adalah, “aku nggak mau hidup bersamamu, karena kamu jelek dan nggak punya iphone, tapi karena aku takut menyakitimu, maka aku bilang saja bahwa kamu terlalu baik buat aku”, itulah semiotika. Gampang, kan? Mari kita menuju pembahasan intinya.
Kata “peh” sebagai kata imbuhan bermakna negatif
Walaupun saya bukan asli dari warga keresidenan Kediri, tapi saya tahu betul perkara “peh” dan “biuh” ini dari kawan-kawan saya yang asli keresidenan Kediri. Oh, ya, for your information aja, istilah keresidenan Kediri ini maksudnya adalah pembagian wilayah administratif yang terdiri dari Kabupaten Kediri, Trenggalek, Blitar, Tulungagung, dan Nganjuk. Jadi, kata “peh” dan “biuh” pasti udah mendarah daging dalam perbendaharaan kata warga atau anak muda keresidenan Kediri.
Oke, balik ke pembahasan. Menurut kawan saya, sebut saja namanya Ihya’, bahwa “peh” itu merupakan kata imbuhan yang bermakna negatif. Misalnya perkataan, “awakmu kok tuolol, sih, peh!”, atau yang lain seperti, “aku wingi i guoblok lo, ape tuku bensin i tapi malah aku melu antrian solar, peh!”. Jadi, kata “peh” itu biasa dipakai sebagai kata imbuhan di akhir kalimat.
Lalu, kenapa bisa bermakna negatif? Nah, mari kita bedah secara semiotika.
Bunyi perkataan tadi, “aku wingi i guoblok lo, ape tuku bensin i tapi malah aku melu antrian solar, peh!”, itu adalah ‘penanda’ sebagai kata imbuhan. Sementara ‘petandanya’, seseorang itu sadar atas kegoblokannya sendiri karena merasa dirinya nggak mampu membedakan mana antrian bensin dan mana antrian solar. Jadi, berdasarkan semiotika, saya menyimpulkan bahwa kata “peh” itu muncul dari kondisi mental yang ngerasa jengkel, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Di sinilah titik negatifnya.
Makanya, kalau kalian hendak menggunakan kata “peh” dalam sebuah kalimat, maka tentukan dulu, apakah mental kalian sedang merasa jengkel atau nggak. Jangan sampai keliru, jangan sampai menyalahi kaidah tata bahasa keresidenan Kediri. Bahaya!
Kata “biuh” sebagai kata imbuhan bermakna hiperbola
Secara popularitas, rasa-rasanya kata kedua asal keresidenan Kediri ini yang paling popular adalah kata “biuh”. Hampir di tiap kejadian atau suasana tertentu, kata “biuh” ini laris jadi modal komunikasi sosial masyarakat Indo, khususnya anak muda sekarang. Penasaran kenapa hal itu bisa terjadi? Mari ikuti analisis saya.
Lagi-lagi supaya ada unsur penelitiannya, saya harus mengambil referensi dari kawan saya yang namanya Ihya’ tadi. Kata dia, “biuh” itu adalah kata imbuhan yang punya makna hiperbola. Misalnya kalimat, “biiiuuhh… kowe buluk ngunu kok iso oleh pacar ayu!”, atau perkataan yang lain, “biuh biuuuhhh… uwapik tenan kui pemandangan e!”. Iya, pokoknya kata “biuh” itu lebih seru digunakan, entah ketika jengkel, takjub, atau hendak mengolok-olok orang. Tapi ingat, penempatan “biuh” selalu di awal kalimat, bukan di akhir seperti “peh”.
Terus, letak hiperbolanya di mana? Lagi-lagi inilah pentingnya menganalisis dengan pendekatan semiotika.
Coba perhatikan kedua kalimat contoh di atas tadi, keduanya secara ‘penanda’ adalah perkataan yang menunjukkan kata seruan terhadap suatu hal. Sementara secara ‘petanda’, kedua kalimat itu bermakna sebagai bumbu-bumbu semacam micin atau royco atas apa yang sedang dirasakan, dilihat, bahkan diraba. Jadi, ketika mengatakan suatu hal yang kesannya seru, itu rasa-rasanya nggak lengkap kalau nggak dilebih-lebihkan dengan menambahkan kata, “biiiuhhh…” atau di-double sampai berbunyi, “biuh biuuuhhhh…..”. Kira-kira begitulah analisis semiotikanya.
“Peh” dan “biuh” sebagai pelengkap kata “cuk”
Dari analisis dan penjelasan terkait “peh” dan “biuh” tadi, kira-kira apakah kedua kata itu akan mengancam eksistensi kata “cuk” sebagai satu-satunya kata umpatan paling popular sepanjang tahun?
Sebagai warga tulen Mojokerto-an yang sedari kecil mengadopsi kata “cuk”, saya nggak menemukan potensi ancaman itu. Justru dengan popularnya “peh” dan “biuh”, saya rasa malah melengkapi horizon kata “cuk” sebagai kata yang memuaskan birahi, mental, dan hasrat saya untuk mengumpat. Nggak percaya? Mari kita terapkan sama-sama.
Kalau ketiganya digabung, maka bunyinya akan begini, “biuh biuuhhh…. baliho nek dalan iki kok akeh tenan cuk, jan-jane kui arep nyaleg opo arep dodolan rai, sih, peh!”.
Nah, kalau itu nggak perlu dianalisis menggunakan teori semiotika, sebab ketika kita mengatakannya dengan penuh semangat Nasionalisme pun udah jelas, bahwa mengumpat dengan komposisi kata peh, biuh, dan cuk adalah sebagian wujud dari pancasila. Jadi, kesimpulan dari penelitian saya ini mengemukakan, bahwa jangan anggap peh dan biuh sebagai ancaman, tapi jadikanlah sebagai pelengkap umpatan khas warga negara Indonesia,

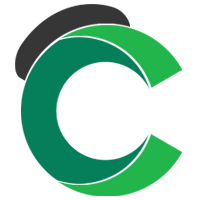

Posting Komentar